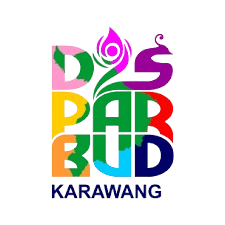PERISTIWA RAWAGEDE 1947
Dharma PGPada masa Agresi Militer II Belanda tahun 1947, Rawagede (sekarang Desa Balongsari), Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah strategis yang dapat dijangkau dengan berbagai kendaraan, termasuk kereta api. Daerah ini sering dijadikan sebagai Markas Gabungan Pejuang (MGP). Rumah salah seorang warga keturunan Tionghoa di sana dijadikan sebagai markas utama, sebab bangunannya besar, permanen, dan dekat dengan stasiun kereta api. Terdapat beberapa kesatuan pejuang yang berkumpul di tempat tersebut, seperti Field Preparation Barisan Hitam “88” DB) yang berubah menjadi S. P, “88” D.B (Satuan Pemberontakan “88” D.B) yang dipimpin oleh A. S. Wagianto/ Usman Somantri; Pasukan Bambu Runcing pimpinan Tjan Samsudin; Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI di bawah pimpinan W. G. Sugianto; dan Markas Pertempuran Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kyai Noer Ali. Kesatuan para pejuang tersebut bergabung dengan Brigade/Resimen 6 Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Lukas Kustario dan melanjutkan perang gerilya melawan tentara Belanda. Antek-antek Belanda mengetahui keberadaan markas tersebut. Pasukan militer Belanda kemudian berencana untuk menyerang wilayah Rawagede, tetapi Kepala Desa Tunggakjati bernama Saukim berhasil menyadap informasi tersebut setelah berpura-pura memihak tentara Belanda. Saukim kemudian memberitahu para pejuang di MGP. Mereka pun menyiapkan diri menghadapi pasukan Belanda. Mereka memblokir jalan yang terhubung ke Rawagede. Dari arah barat, Jalan Cilempuh diputus. Di sisi lain, Jalan Palawad yang berada di arah selatan juga diputus. Selanjutnya dari arah timur dan utara Jembatan Garunggung dibongkar. Namun pembongkaran ini tidak berhasil. Kemudian mereka memutus jalan yang menghubungkan jembatan tersebut dari dua arah. Serangan Belanda ke Rawagede pun gagal. Kewaspadaan kemudian meningkat, mengingat serangan mendadak bisa saja terjadi. Para pejuang berpatroli secara bergiliran. Ketika berpatroli, ada pejuang yang menangkap seorang bumiputera yang menjadi intel Belanda. Orang tersebut kemudian diinterogasi setelah dibawa ke markas. Saat itu, Lukas Kustario, Komandan Brigade I, Resimen 6 Divisi Siliwangi dan pasukannya sedang ada di markas. Bersama Lurah Suminta, Wakil Lurah Iyob Armada, dan para pejuang, Lukas Kustario kemudian berunding dan berencana memindahkan semua senjata dan pasukan dari Rawagede ke Tunggakjati. Mereka yang telah diketahui Belanda kemudian melanjutkan perjalanan ke Tunggakjati. Dalam rombongan itu terdapat pasukan bersenjata dari berbagai badan kelaskaran. Di Rawagede saat itu hanya tersisa pasukan tanpa senjata dan para pamong desa. Tentara Belanda dalam kelompok Resimen Infanteri IX yang dipimpin oleh Mayor Wijman mengejar pasukan yang dipimpin Lukas Kustario. Mereka berhasil sampai di Rawagede tetapi tidak menemukan Lukas Kustario bersama anggota pasukannya. Suara tembakan terdengar membabi-buta. Para lelaki di desa itu dipaksa untuk mengatakan keberadaan Lukas Kustario, tapi tidak satupun dari mereka mengatakannya. Banyak peluru yang melesat ke arah rumah-rumah penduduk, pohon-pohon, dan binatang peliharaan. Tentara Belanda juga menggeledah rumah-rumah penduduk untuk menemukan para pejuang. Laki-laki dewasa yang ditemukan di dalam rumahnya akan dibawa keluar dan dipaksa mengangkat tangannya ke atas kepala. Jika melawan atau melarikan diri, mereka akan ditembaki hingga mati. Mereka yang tertangkap akan dikumpulkan di pekarangan rumah atau tempat yang cukup luas. Mereka juga dipaksa untuk berbaris menghadap ke belakang. Satu persatu dari para laki-laki itu ditembaki dari jarak 3 meter. Namun sebelumnya, mereka akan ditanya satu persatu tentang keberadaan Lukas Kustario dan para pejuang. Tidak mendapatkan jawaban dan informasi, tentara Belanda pun semakin murka. Mereka kemudian menembak para lelaki itu. Sementara itu, para perempuan, anak-anak dan laki-laki berusia lanjut dibiarkan untuk berdiam diri di rumah. Tentara Belanda juga membakar rumah penduduk jika menemukan adanya lambang-lambang republik dan simbol-simbol kelaskaran. Beberapa rumah yang dibakar adalah rumah Lurah Suminta, Lurah Iyo Armada, dan Gouw Kim Wat, seorang keturunan Tionghoa, serta beberapa rumah lainnya. Belanda yang murka juga mengobrak-abrik Rawagede. Mereka juga masuk ke kandang-kandang ternak, semak belukar, dan tepi-tepi sungai sambil membawa anjing pelacak. Berdasarkan keterangan para saksi sejarah, jika saat itu Belanda tidak membawa anjing pelacak, bisa jadi masih banyak jiwa yang selamat dan tidak tertangkap. Beberapa penduduk juga bersembunyi di sungai dan menutup kepalanya dengan eceng gondok dan rerumputan. Namun anjing pelacak dapat menemukan tempat persembunyian mereka dan menggonggong di area itu. Tentara Belanda kemudian menembak ke arah tempat persembunyian tersebut. Suhanda, salah seorang saksi sejarah mengatakan bahwa ia yang bersembunyi di sungai langsung muncul ke permukaan dengan tangan di atas kepala karena takut ditembak. Ia bersama dua temannya dibawa ke lapangan dan dibariskan dengan orang-orang yang sudah tertangkap lebih dahulu. Mereka disuruh menghadap pagar dengan tangan di atas kepala. Tentara Belanda saat itu siap menembak. Komandan mereka memberikan aba-aba sambil berhitung. Pada masa itu Suhanda dapat melarikan diri dengan meloncati pagar bersama dua orang temannya. Sayangnya, kedua orang temannya mati tertembak. Saih, salah seorang saksi sejarah yang lain, saat itu berusia 22 tahun. Ia bersama Rohim, teman sebayanya sedang berjalan tergesa-gesa di sekitar sungai. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan Belanda menyebar dengan cepat. Mereka juga mendengar rentetan tembakan dan erangan kesakitan para warga. Saih juga saat itu digiring ke halaman sebuah rumah penduduk. Berdasarkan penuturannya, sekitar 10 pria saat itu telah berjajar dan berjongkok dalam 2 barisan. Dalam barisan itu terdapat Locan, ayahnya. Saih kemudian didorong untuk berjongkok di sisi yang lain. Mereka dibentak dan ditanyai keberadaan para tentara pejuang. Tentara Belanda menghantam pelipis orang-orang itu dengan popor senjatanya, tetapi tidak ada jawaban yang terdengar. Beberapa saat kemudian suara tembakan tedengar. Saih saat itu segera merebahkan diri ke depan, lalu ada sesosok tubuh yang menimpa badannya dari samping. Telapak tangan dan punggungnya terkena peluru. Ia berpura-pura mati hingga para tentara Belanda tidak terdengar lagi ada di sekitarnya. Setelah itu, Saih pun berusaha untuk pulang dan mengabari ibunya bahwa ayahnya tewas. Para laki-laki yang dikumpulkan oleh tentara Belanda itu juga disuruh berbaris dan diperintahkan untuk berjongkok. Mereka diberondong hingga mati. Mayat mereka berserakan, bahkan sebagian ada yang dihanyutkan di Kali Rawagede. Mayat-mayat yang tidak dihanyutkan kemudian dikumpulkan oleh para wanita di kampung dan dikuburkan sebisa mereka. Di sana tidak ada laki-laki dewasa yang hidup. Semuanya telah dihabisi. Saat itu Kampung Rawagede hanya dihuni perempuan dan anak-anak. Ini adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung karena tidak dapat menyerahkan Lukas Kustario kepada tentara Belanda. Suhanda juga mengatakan bahwa waktu itu banyak sekali serdadu dan algojo yang ada di Rawagede. Aksi pembantaian mereka begitu kejam sehingga nyawa manusia diibaratkan seperti nyawa binatang yang tidak berarti. Belanda masih belum puas dengan pembantaian itu karena sebagian pejuang dan Lukas Kustario gagal dibunuh. Pasukan Belanda juga bertambah banyak dan dikerahkan untuk terus memburu Lukas Kustario. Pagi itu di Rawagede diguyur hujan deras. Di sana terdengar tangis histeris para wanita yang suami dan orangtuanya meninggal. Para wanita kemudian berupaya mengumpulkan dan mengubur jenazah keluarga masing-masing. Banyak juga jenazah yang tidak ditemukan karena terbawa arus sungai dan hanyut. Gambaran peristiwa pembantaian di Rawagede dapat dilihat dalam relief yang menampilkan 3 orang lelaki yang berdiri sambil memegang senjata. Tidak jauh dari situ terdapat beberapa perempuan yang bersimpuh dan merangkul jasad. Dalam peristiwa pembantaian itu, terdapat 431 warga yang menjadi korban. Kemudian terdapat 5 orang yang dibawa hidup-hidup oleh tentara Belanda. Para korban meninggal yang dikumpulkan dimakamkan dalam satu area. Kemudian pada 1951 makam mereka dipindahkan ke Taman Makam Sampurnaraga yang kini berada di area Monumen Rawagede. Referensi: Moses, A. Dirk, Bart Littikhuis, Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia, New York: Routledge 2018. Ismail, Asih Widiarti, dkk., Tragedi Rawagede dan Misteri Kapten Lukas, Jakarta: Tempo Publishing, 2023. Maluwi Saelan, Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ’66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa, Jakarta: Visimedia, 2008. Nina Herlina Lubis, Adeng, Etty Saringendyanti, dkk., Sejarah Kabupaten Karawang, Karawang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, 2011. Yuda Febrian Silitonga, Willy Firdaus, dan Dharma Putra Gotama, Rengasdengklok Undercover: Menggali Makna “Karawang Pangkal Perjuangan”, Purwakarta: CV. Pustaka Press, 2018.

Komentar
- Previous
- 1
- Next